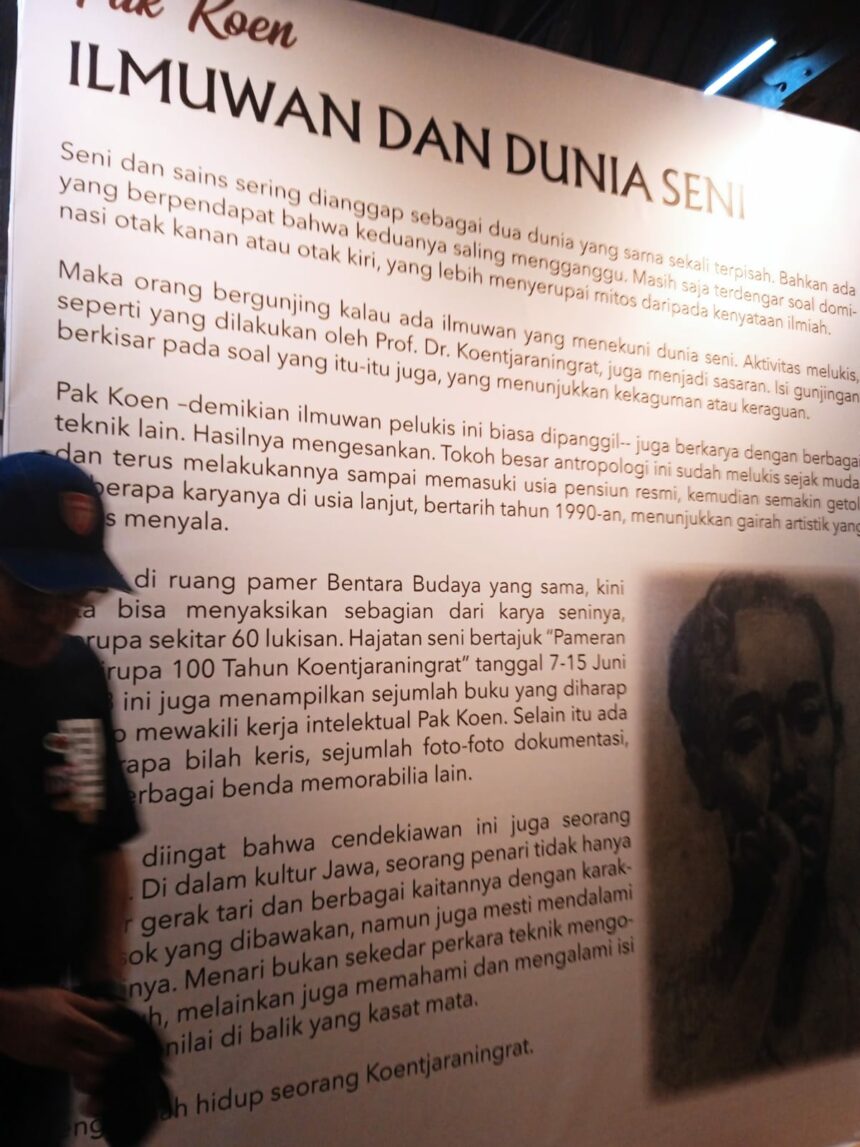Antropolog Indonesia Koentjaraningrat tidak saja menunjukkan bahwa Seni dan Sains tidak berseberangan, namun juga mengajarkan kepada kita bahwa Antropolog sejati seungguhnya seorang aktivis.
Oleh Benjamin Tukan
Nama Koentjaraningrat memang tidak asing bagi masyarakat pendidik di Indonesia. Sejak bangku sekolah menengah, saat siswa mulai diperkenalkan dengan ilmu Antropologi atau hal yang menyangkut budaya, Koentjaraningrat diperkenalkan sebagai Bapak Antropologi Indonesia.
Seminggu yang lalu, tepatnya 8 hingga 15 Juni 2023, Bentara Budaya Jakarta menggelar 100 tahun Koentjaraningrat. Berbagai acara digelar menyertai peringatan ini seperti, pameran lukisan, bedah buku, dan diskusi seni. Acara dibuka Dirjen Kebudayaan Hilmar Farid, dan diakhiri dengan pementasan Wayang Orang Bharata.
Baik yang datang berkunjung ke pameran ini, maupun apa yang ditampilkan dalam pameran menunjukkan bahwa sosok Koentjaraningrat memang perlu dikenang oleh bangsa ini. Sosok yang memberi sumbangan besar pagi ilmu pengetahuan di Indonesia. Antropolog yang berperan besar dalam mendeskripsikan sejarah dan kebudayaan Indonesia.
Mencintai Budaya Sejak Kecil
Prof. Dr. Koentjaraningrat yang lebih akrab disapa oleh mahasiswanya dengan sapaan Pak Koen, lahir di Yogyakarta 15 Juni tahun 1923. Ia lahir dalam keluarga bangsawan. Ayahnya R.M.Ng. Emmawan Brotokoesomo, adalah seorang pamong praja di lingkungan Pakualaman. Ibunya, R.A. Pratisi Tirtotenojo, adalah penerjemah bahasa Belanda pada keluarga Paku Alam.
Lingkungan keraton yang diakrabi sejak kecil, berpengaruh pada pengenalan dan kecintaannnya pada seni dan kebudayaan. Ia juga mencintai buku dan munjukan bakatnya sebagai seorang ilmuwan. Di masa rkecil, Pak Koen senang datang ke rumah seorang dokter keturunan Tionghoa untuk membaca berbagai buku termasuk disertasi tentang antropologi dari pakar terkenal.

Cinta ilmu, membawa Pak Koen menjadi pribadi yang disiplin dan mandiri. Pada usia 8 tahun, ia mengenyam pendiidkan di Europeesche Lagere School . Setelah lulus ia melanjutkan sekolah ke MULO, kemudian ke Universitas Gadjah Mada dengan mengambil jurusan sastra Indonesia. Ia memperoleh gelar sarjana muda tahun 1950 dari kampus ini. Ia baru meraih gelar Sarjana Sastra Bahasa Indonesia dari Universitas Indonesia tahun 1952.
Dari Universitas Indonesia, Pak Koen kemudian meraih gelar Master of Arts di bidang Antropologi, dari Yale University pada 1956 dan meraih gelar Doktor Antropologi di Fakultas Sastra Universitas Indonesia pada 1958.
Ketertarikan pada bidang antropologi dimulai sejak menjadi asisten Prof. G.J. Held, guru besar antropologi di Universitas Indonesia, yang mengadakan penelitian lapangan di Sumbawa.
Sebagai dosen di Universitas Indonesia, pak Koen dikenal sebagai sosok yang sederhana, dan sangat dekat dengan mahasiswanya. Perhatian pada bidang antropologi, membawanya untuk merintis berdirinya sebelas jurusan antropologi di berbagai universitas di Indonesia, diantaranya, Universitas Indonesia, Universitas Gadjah Mada (Yogyakarta), Universitas Udayana (Denpasar), Universitas Hasanudin (Ujung Pandang), Universitas Pajajaran (Bandung), Universitas Cendrawasih (Jayapura).
Sepanjang hidupnya Pak Koen mendedikasikan untuk perkembangan Ilmu Antropologi, pendidikan Antropologi dan segala sudut pandang yang berkaitan dengan kebudayaan dan kesukubangsaan di Indonesia. Ia mahir berbahasa Belanda dan Inggris juga tekun menulis.
Sejak tahun 1957 hingga 1999, ia telah menghasilkan puluhan buku serta ratusan artikel.Beberapa karya tulisnya telah menjadi rujukan bagi dosen, mahasiswa, ilmuwan Indonesia maupun asing, juga masyarakat umum. Melalui tulisannya, ia mengajarkan pentingnya mengenal masyarakat dan budaya bangsa sendiri.

“Buku-buku Pak Koen tidak hanya menjadi acuan bagi mereka yang belajar antropologi secara formal, tetapi juga bermanfaat untuk digunakan bagi siapa saja yang coba memahami masyarakat secara holistik komperehensif dalam balutan budaya,” tulis Pinky Saptandari, dalam buku “Seabad Koentjaraningrat: Persembahan dan Kenangan”, yang diluncurkan pada rangkaian acara 100th Koentjaraningrat
Selain mengajar Antropologi di Fakultas Sastra Universitas Indonesia, ia juga pernah bertugas sebagai tenaga riset dan Antropologi di University of Pittsburgh, Amerika Serikat (1961-1962); guru besar di Utrecht University, Belanda (1966-1967); guru besar tamu di University of Illinois, Amerika Serikat (1968); guru besar tamu di University of Wisconsin, Amerika Serikat (1980); serta mengajar di Universitas Malaya, Kuala Lumpur (1971-1973 dan (1975-1977).
Dedikasinya dalam perkembangan ilmu Antropologi di Indonesia ini mengantarkannya ke berbagai penghargaan, diantaranya, penghargaan Grand Prize dari 6th Fukuoka Asian Cultural Prizes pada 1955. Di dalam negeri sendiri, anugerah Satyalencana Dwidja Sistha dari Menteri Pertahanan dan Keamanan Repulik Indonesia didapatkan pada tahun 1968. Pak Koent juga menerima gelar kebangsawanan Kanjeng Pangeran Haryo (KPH) dari Sri Paduka Pakualam VIII pada 1990 di Kadipaten Pakualaman, Daerah Istimewa Yogyakarta.
Antropolog pertama Indonesia ini meninggal dunia dalam usia 75 tahun, Selasa 23 Maret 1999 sekitar pukul 16.25, di RS Kramat 128, Jakarta Pusat. Dia telah terkena stroke sejak 1989. Dimakamkan di TPU Karet Bivak, Rabu 24 Maret 1999 sekitar pukul 13.00.
Sisi Lain
Pak Koen dikenal sebagai ilmuwan, dosen dan dikenal sebagai Bapak Antropologi Indonesia. Tema-tema penting yang selalu diingat dari Pak Koen adalah hubungan manusia dan kebudayaan. Defenisi Kebudayaannya adalah keseluruhan sistem gagasan, tindakan, dan hasil karya manusia dalam rangka kehidupan masyarakat yang dijadikan milik manusia dengan belajar.
Dari situ lalu dikenal dari Pak Koen adalah tiga wujud kebudayaan yaitu ide berupa gagasan/konsep yang abstrak, aktivitas atau kegiatan perilaku manusia, dan benda-benda material hasil karya manusia atau produk budaya yang dapat dilihat dengan indera penglihatan.
Tiga wujud tersebut lantas dipecah lagi menjadi tujuh unsur universal, yaitu sistem religi dan upacara keagamaan, sistem dan organisasi kemasyarakatan, sistem pengetahuan, bahasa, kesenian, sistem mata pencaharian hidup, dan sistem teknologi dan peralatan.
Selly Riawati dalam buku “Seabad Koentjaraningrat: Persembahan dan Kenangan”, menyebut peranan Pak Koen dalam perkembangan antropologi di Indonesia sangatlah menyeluruh, tidak tertandingi sampai kini.
“Mulai dari mengajar,menulis buku dengan berbagai fungsi(pengantar, metode, teori, penerapan antropologi, tulisan popular tentang kebudayaan dan mentalitas, kajian etnisitas dan nasionalisme), menyekolahkan dosen, mendukung pembangunan jurusan/departemen antropologi di Tanah Air, membangun jurnal dan asosiasi profesi antropologi,” tulis Selly Riawati, salah satu mahasiswa Koentjaraningrat.
Menyertai sosoknya sebagai seorang ilmuwan, Pak Koen juga seorang yang memiliki bakat melukis, menari dan terlibat dalam perjuangan di saman revolusi kemerdekaan RI. Dari melukis, ia menghasilkan karya seni dengan medium cat air. Karya –karya itu terpampang dalam pameran 100th Koentjaraningrat di Bentara Budaya, Jakarta.
Sementara dalam soal seni tari, Pak Koen punya keahlihan menari Jawa dan punya predikat sebgai instruktur tarian Jawa. Ia dan kelompok tarinya beberapa kali mengikuti pementasan tari, termasuk mengisi acara pertemuan negosiasi antara pemerintah Indonesia dengan Belanda yang diselenggarakan di Yogyakarta.
Dalam perjuangan semasa kemerdekaan, Pak Koen yang kala itu sebagai asisten di perpustakaan Museum Nasional di Jakarta, ikut menyelamatkan buku-buku yang tidak disukai Jepang, terutama buku berbahasa Belanda dengan mengirim ke Yogyakarta. Buku-buku inilah yang kemudian menjadi koleksi awal perpustakan UGM.
Pak Koen selalu menampilkan sosok dirinya yang konsisten, selayaknya seorang aktivis. Untuk maksud ini, dalam bagian Pendahuluan buku “Seabad Koentjaraningrat: Persembahan dan Kenangan”, ditulisakan sebagai berikut:
“Jalan antropologi yang ditempuh Koentjaraningrat adalah jalan aktivis sebagai seorang pioner, seorang yang harus melakukannya atas dasar cita-cita yang bukan pilihannya, kecuali harus dijalani sebagai misi hidup. Momen krusial sorang Koentjaraningrat sebagai aktivis mungkin dimulai ketika ia menolak perintah Jepang untuk memusnahkan buku-buku berbahasa Belanda. Koentjaraningrat juga menjadi peluki poster perjuangan, dan di masa damai Indonesia merdeka ia berdiri di depan untuk meyakinkan dan mencegah pemerintah Indonesia membuang antropologi ke keranjang sampah sebagai ilmu warisan kolonial.”

Penjelasan yang lebih lengkap dibaca dalam artikel pertama buku “Seabad Koentjaraningrat: Persembahan dan Kenangan” yang ditulis Surya A. Afiff, di bawah judul ” Mengingat Koentjaraningrat dari Lensa Aktivisme”.
Surya A. Afiff menulis : ” Saya termasuk sepakat dengan mereka yang berpendapat bahwa antropologi dan aktivisme tidak memiliki batas yang tegas, tetapi sering kali berkelindan, Menurut sebagian antropolog, aktivisme pada dasarnya bagian yang integral dalam sejarah antropologi, meskipun sering kali hal ini tidak selalu secara eksplisit diakui secara terbuka (Willow & Yotebieng, 2020:4).”
Menurut Surya A. Afiff, sering kali pembahasan tentang aktivisme dikaitkan dengan gerakan sosial, namun pengertian aktivisme lebih luas dari sekadar hanya membatasi pada ruang lingkup kegiatan satu gerakan sosial yang terorganisasi.
Dengan menggunakan pengertian aktivisme sebagai tindakan yang dilakukan individu untuk menghasilkan suatu perubahan sosial, Surya A. Afiff mengatakan bahwa kiprah kerja Pak Koen dan kontribusinya dalam membangun antropologi di Indonesia dapat juga dipandang memiliki dimensi aktivisme.
Eratnya antropologi dengan aktivisme dapat dicontohkan dari yang dilakukan Antropolog Amerika Serikat, Franz Boas. Meskipun, kata Surya A. Afiff, tidak dapat disamakan dengan Franz Boas, tetapi pandangan adanya semangat aktivisme tetap melekat pada kerja dan kiprah Pak Koen di masa hidupnya.
Seratus tahun Koentjaraningrat, sungguh penuh kenangan. Walau Koentjaraningrat sosok yang sudah terlampau dikenal dan pantas untuk dikenang, namun ada satu hal yang masih tersisa, adalah sosok dirinya yang sederhana namun telah memberikan kontribusi yang besar bagi masyarakat Indonesia.
Yunita T. Winarto, dalam salah satu artikel buku “Seabad Koentjaraningrat: Persembahan dan Kenangan”, menulis : “Siapa nyana, dalam tubuh berpenampilan sederhana itu, terpancar daya karismatik yang kuat dan pribadi yang teguh kukuh, konsisten dengan pendiriannya, dan selalu berpikir kreatif mencari solusi bagi upayanya menumbuhkembangkan generasi penerus antropologi” .