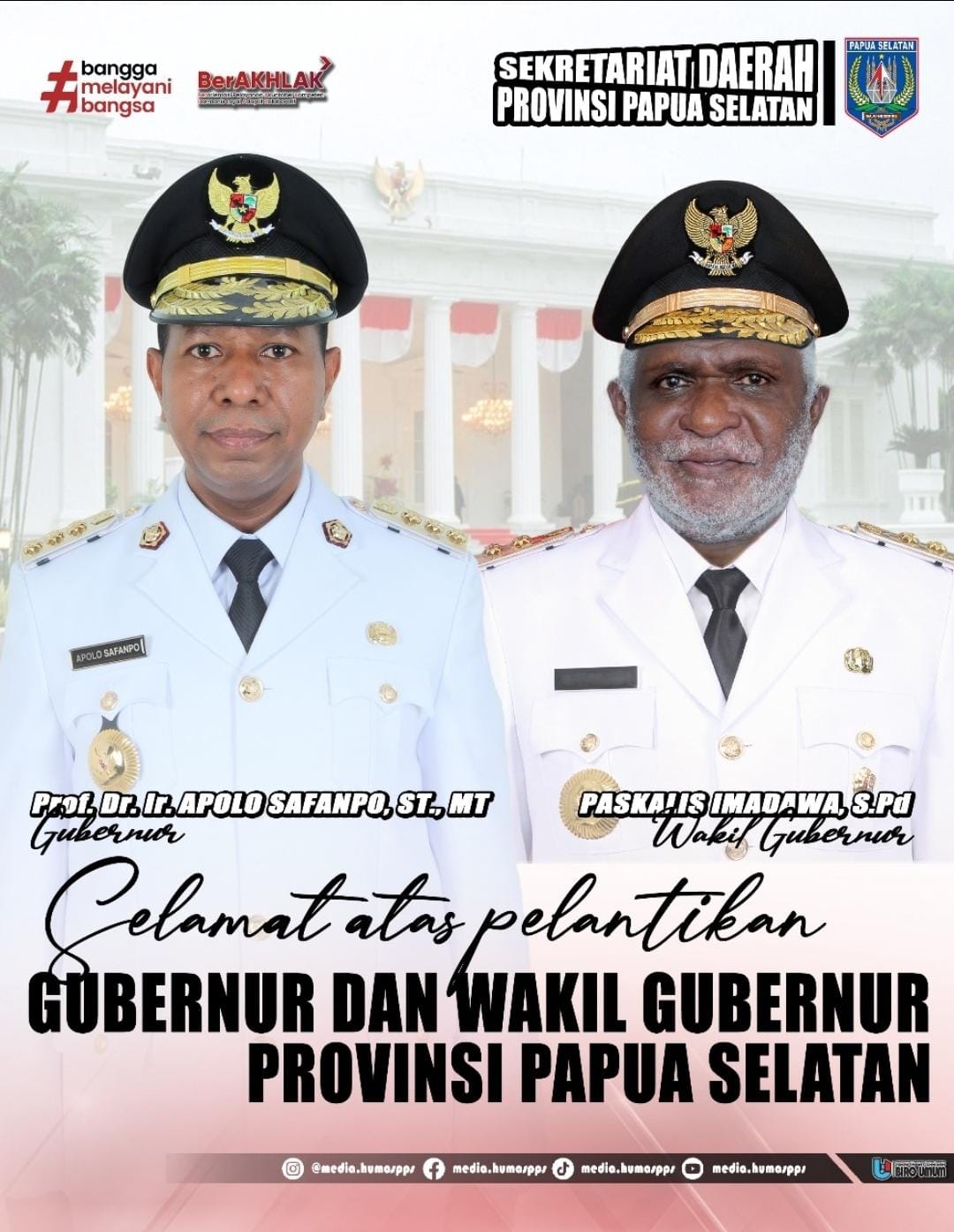TIFFANEWS.CO.ID,- Meskipun telah ternama sebagai sastrawan, intelektual, pejuang demokrasi yang mendapat penghargaan dalam dan luar negeri, pendiri majalah Tempo Goenawan Mohamad baru mulai menulis novel di usia lanjut. Di Novel yang ia luncurkan ini, terdapat kalimat yang cukup menyentuh, “Yang kita butuhkan bukan pendekar perang.” “Lalu apa?” “Kemauan politik—yang terkadang ada, terkadang tidak..”
Novel pertamanya, Surti + Tiga Sawunggaling, diterbitkan tahun 2018, tahun ia berusia 77. Novel keduanya, Manurung: Sebuah Montase, terbit tahun 2025 ini; ia berumur 84.
Pada periode yang kurang lebih sama, ia juga masuk ke dunia seni rupa (melukis, membuat karya grafis maupun instalasi) dengan sangat produktif. Ini tentu saja merupakan contoh tenaga kreatif yang tak pudar di usia lanjut yang bisa menjadi inspirasi bagi generasi yang lebih muda.
Novel Manurung: Sebuah Montase yang diluncurkan ini mengambil waktu era Perang Dingin, suatu babak sejarah dunia yang sangat penting tapi sering dianggap telah lewat dan dilupakan oleh generasi sekarang.
Karel Manurung, tokoh utama novel ini, mencari adiknya yang hilang. Abang adik ini adalah eksil Indonesia di Eropa. Ayah mereka dibunuh dalam peristiwa penumpasan PKI 1965-1966. Karel terdampar di Jerman Timur, Yosef di Czekoslovakia (dua negara Blok Timur itu kini telah tidak ada. Jerman Timur bersatu dengan Republik Federal Jerman. Czekoslovakia terpecah menjadi Ceko dan Slovakia). Karel direkrut menjadi informan Stasi, badan intelijen Jerman Timur, membuat novel ini bernuansa spionase yang lembut.

Sementara itu, Yosef justru terlibat demonstrasi anti Uni Soviet di Praha tahun 1968—suatu peristiwa yang dikenang sebagai Musim Semi Praha yang singkat dan berakhir tragis. Kesedihan dan kecemasan menjadi perasaan mendasar Karel yang rindu sekaligus tahu bahwa Yosef dalam bahaya. Karel sendiri mendapat tugas rahasia kecil dari badan intelejen untuk “menghidupkan kembali komunisme” di Indonesia. Akankah Karel menemukan Yosef menjadi penggerak utama cerita ini.
Tapi, sebagaimana tulisan-tulisan GM yang lain, karya ini tak bisa tidak menekankan perenungan. Perenungan filosofis yang biasa terdapat dalam Catatan Pinggir atau esaiesai GM lain, kini hadir dalam bentuk dialog atau surat-menyurat antar tokoh-tokoh novel.
Peluncuran di Teater Utan Kayu, Jakarta Novel ini pernah diluncurkan di Yogyakarta sebelumnya. Peluncuran di Jakarta diadakan pada hari Sabtu, 26 April 2025, pukul 15:00, di Teater Utan Kayu. Petikan dari novel itu dibacakan oleh aktor Syam Anchoe Amar dan Ruth Marini. Ulasan tentang novel ini diberikan oleh Ayu Utami, novelis yang sejak 2021 memberikan hadiah sastra tahunan untuk pemula bernama hadiah sastra Rasa.
Ulasan Ayu Utami
Ayu Utami berpendapat bahwa tema novel ini sangat penting agar kita tidak melupakan Perang Dingin, sebab perang itu, meski dianggap telah selesai, masih membentuk dunia hari ini. Runtuhnya Uni Soviet dan blok Timur di peralihan 1980 ke 1990, yang di masa itu disambut sebagai “angin baru” dan kemenangan demokrasi, ternyata tidak hanya membawa kebaikan saja, tetapi juga melahirkan perang-perang baru, kekejaman baru, sering atas nama agama dan etnisitas, serta kapitalisme-liberalisme yang tanpa penantang sehingga menimbulkan ketimbangan-ketimpangan baru yang semakin lebar
Novel Manurung, yang mengambil latar hingga tahun 1970-an awal, memang tidak menyentuh secara langsung apa yang terjadi pasca runtuhnya Uni Soviet dan Blok Timur 20 tahun kemudian. Tapi, perdebatan dan renungan yang relevan sampai masa sekarang muncul dalam percakapan para tokohnya. Kritik pada kapitalisme banyak muncul dalam percakapan mengenai arsitektur dan kota antara Karel dan atasannya di Bauakademie, Farhad Hamedani, seorang pelarian dari Iran.
Kenapa arsitektur jadi percakapan penting di Berlin? Di seberang Tembok, di dunia borjuis, orang menganggap arsitektur kecerdasan mendesain gedung dengan gaya ini atau itu. Di sini tidak. Di sini arsitektur perjuangan menciptakan ruang agar manusia saling percaya, saling ketemu, saling membantu. (hal.53)
Di pihak lain, kritik terhadap program sosialisme dan komunisme partai bermunculan dalam percakapan para tokoh, juga dalam momen intim abang-adik atau sebelum atau setelah percintaan dengan kekasih. Itu membuat percakapan filosofis intelektual terjalin secara lembut, tidak memaksa, bahkan dengan rasa sendu. Seperti antara Yosef dan Renatka, yang menjadi aktivis anti kebengisan Partai Komunis Czekoslovakia:
“Yang kita butuhkan bukan pendekar perang.
” “Lalu apa?”
“Kemauan politik—yang terkadang ada, terkadang tidak.”
Malam itu juga Renatka mengajaknya ke sebuah kamar di sudut selatang asrama. Mereka bercinta, lelah, merokok, minum bir, mendengarkan Janis Joplin, lalu Renatka memberinya sebuah notes kecil. “Buku ini 56 halaman. ditulis tangan, sebanyak tiga kopi, dan aku ingin kau pegang satu. Kau harus selamatkan jika aku terpaksa melenyapkan edisi yang lainnya.
” “Apa isinya?” “
Antara lain sejumlah nama dan alamat. Mereka orang Partai, guru besar, anggota CSM, organisasi pemuda komunis, beberapa perwira Angkatan Udara, dan lain-lain yang diam-diam mendukung kami.
” Lima detik jantung Yosef berdebar. (hal. 40-41)
Komunisme dan kapitalisme mendapatkan porsi kritik. Kritik pada kapitalisme biasanya datang dari kecenderungan sosialis tokohnya (hampir semua tokoh di sini cenderung sosialis). Di pihak lain, kritik pada doktrin komunisme dan sosialisme datang dari pengalaman konkret ketubuhan—tubuh, yang tak bisa ditertibkan. Dengan demikian, dekat dengan kritik eksistensialisme terhadap rasionalisme. Di sana-sini kita bisa menemukan “Catatan Pinggir hadir kembali, seperti dalam kutipan yang mengkritik sistem borjuis-kapitalis maupun sosialis-komunis yang menekankan rencana dan ketertiban:
Bangunan bukan hasil, melainkan proses. Bangunan terus-menerus dibentuk dan membentuk penghuninya, dan terus menerus berkembang. Memang, prosesnya ditentukan dari atas. Boulevard Paris diubah besar-besaran oleh Baron de Haussmann; Karl Marx-Allee oleh Henselmann. Di atas itu yang dicatat sejarah baron dan birokrat dan kekuasaan politik dan modal. Tapi Paris dan Berlin dan New York tak hanya terjadi di atas. Atas tak bsia menentukan semuanya. Di bawah ini, bumi bandel dengan segala yang ruwet, jorok, tak pasti–seperti tubuh kita yang tak selalu bisa diatur Tuhan atau Stalin. (hal. 53)
Perihal bentuk
Ayu Utami, yang telah mengikuti dari dekat, tulisan-tulisan GM selama ini, berpendapat bahwa salah satu peran GM dalam sejarah sastra Indonesia adalah menetapkan standar penulisan baru penulisan yang puitis. Sebelumnya, bahasa cenderung diperlakukan sebagai sekadar alat mengantarkan ide-de atau konsep-konsep jadi. Dalam tulisan GM, ide dan konsep lahir bersama pergulatan bahasa. Sejak GM, terutama dengan konsistensi Catatan Pinggir-nya yang terbit di majalah Tempo, prosa liris menjadi standar baru. Itulah pembaruan bentuk yang datang bersama GM.
Menganalisa tulisan-tulisan GM sebelumnya, Ayu pernah mencirikan tiga hal yang menjadi arah pencarian dalam bentuk tulisan GM: 1) kebebasan/emansipasi, 2) model pemahaman yang bukan batasan, definitif, 3) pengutamaan pada pengalaman konkret. Tiga hal itu menghasilkan bentuk tulisan fragmen atau montase atau mozaik, yaitu kepingkeping pendek, yang berhubungan satu sama lain bukan secara argumentatif melainkan asosiatif.

Subjudul Sebuah Montase pada novel Manurung memperkuat tesis ini. Yaitu, sebuah novel yang terdiri dari keping-keping bab pendek, berhubungan tidak dengan ketat linear, melainkan asosiatif dalam melahirkan suasana. Suasana utama itu adalah renungan yang murung—yang bukan mustahil mengakibatkan pemilihan judul dan nama tokoh Manurung (renung, murung, Manurung).
Novel ini ditulis dengan dua warna tinta. Tinta hitam untuk kisah Manurung di Eropa, yang menjadi kerangka utama novel. Tinta merah-oranye untuk surat ibundanya dari Jawa, bercerita tentang peristiwa-peristiwa yang tak selalu berkaitan dari segi tokoh, namun konsisten secara puitis membangun suasana murung (melankoli).
Menurut Ayu, dalam seluruh kekaryaan GM, bentuk fragmen dan suasana murung ini punya dasar filosofis yang dalam. Yatu, kesadaran akan “kemustahilan bahasa”. Yaitu, bahwa bahasa, satu-satunya sarana berpikir manusia, sebenarnya tidak memadai dan tidak bisa dipercaya 100%. Ini membedakan novel GM dan novel-novel murung atau depresif yang tak mencapai kedalaman filosofis, yang tertahan pada level depresi mental, yang biasanya berakhir dengan jalan buntu dan bukannya paradoks, yang banyak terbit di dalam maupun di luar negeri.
Pengarang yang serius, menurut Ayu, biasa mencari bentuk yang cocok untuk pemikirannya atau bereksperimen dengan bentuk-bentuk yang menantang apa yang dianggap mapan. Bentuk tulisan GM yang puitis dan fragmentis bukan sekadar eksperimen menantang kemapanan bentuk yang linear solid yang biasa dipakai dalam novel modern yang dianggap besar. Bentuk montase ini datang dari kesadaran filosofis yang dalam bahwa bahasa tidak memadai sehingga manusia pun harus tetap punya daya kritis terhadap bahasa, yaitu pikiran, tanpa menyingkirkan rasionalitas.
Goenawan Mohamad: Lahir di Batang, 29 Juli 1941. Saat masih kanak, ayahnya, seorang pejuang republik, dibunuh tentara Belanda dalam agresi militer. Di masa muda, ia ikut merumuskan “Manifes Kebudayaan” (1963), yang menolak politik kekuasaan pada kesenian, menyebabkan ia diintimidasi pendukung Sukarno dan PKI.
Di masa presiden Soeharto, ia mendirikan majalah Tempo (1971). Ketika majalah Tempo dibredel tahun 1994, GM menolak tekanan untuk kompromi dan memilih melawan pemerintah. Di seputar era Reformasi, ia ikut mendirikan Komite Independen Pemantau Pemilu dan beberapa organisasi untuk demokrasi lain.
Komitmennya akan pemikiran, demokrasi, kebebasan pers dan ekspresi, mengantarnya pada banyak penghargaan dari luar negrei, antara lain A. Teeuw Award (1994), Wertheim Award (2005), Japan Foundation Award (2022), dan “Official Cross of the Order of Isabel la Católica” (2025, dari Kerajaan Spanyol). (*)